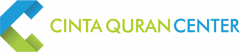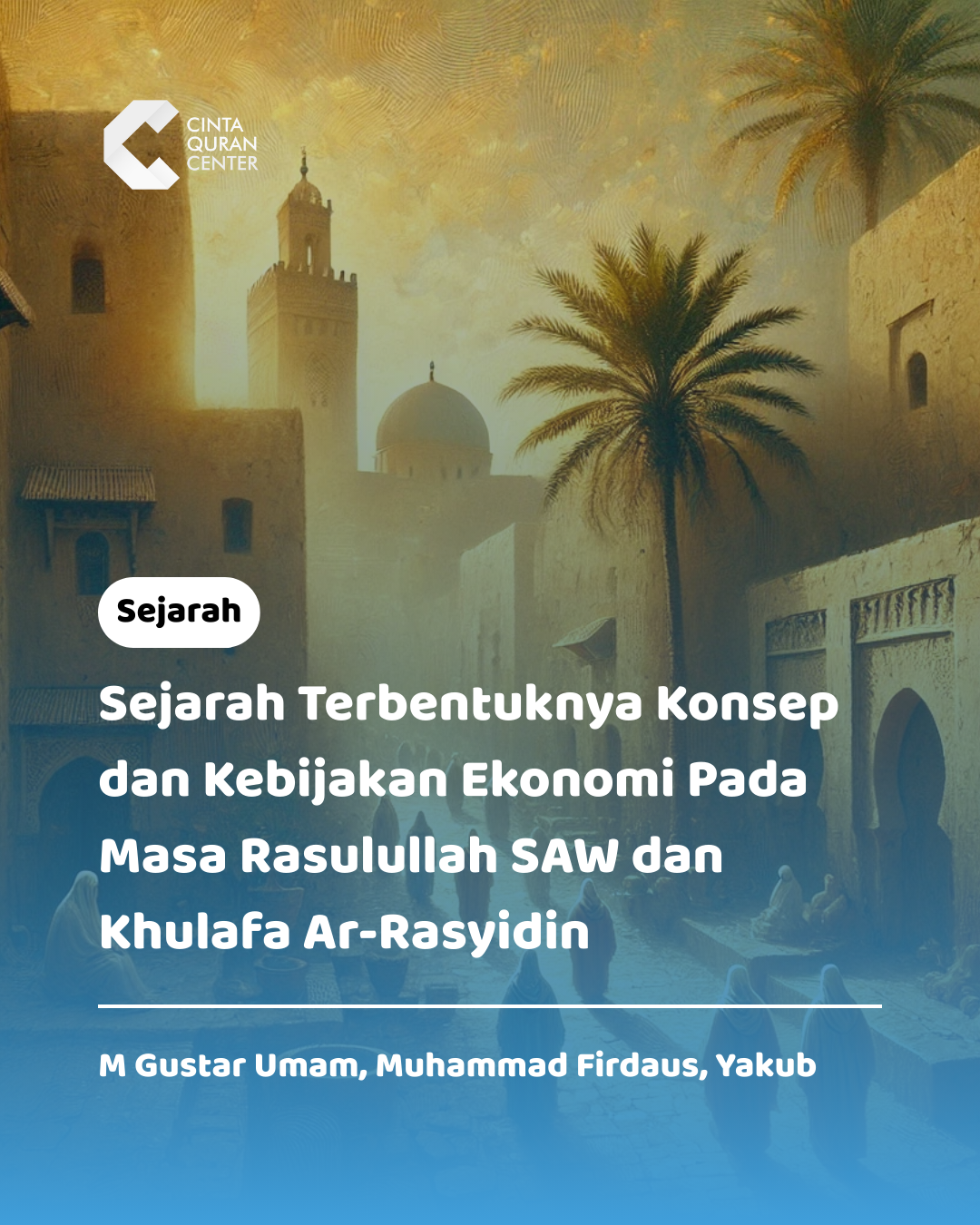Sejarah Terbentuknya Konsep dan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin
M Gustar Umam, Muhammad Firdaus, Yakub
Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
m.gustarumam24@mhs.uinjkt.ac.id, muhammad.firdaus@uinjkt.ac.id, hmyakub1962@gmail.com
Islam adalah agama yang memiliki konsep kehidupan yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek mulai dari spiritual, sosial, hingga ekonomi. Konsep Syumuliatul Islam atau Islam yang bersifat universal dan komprehensif menjadi dasar dalam membangun tatanan kehidupan yang seimbang dan berkeadilan, termasuk dalam bidang ekonomi. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga mengatur interaksi antar manusia (hablum minannas) dengan prinsip-prinsip syariat yang jelas.
Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat keseimbangan antara naqli (ajaran wahyu) dan penalaran aqliyah (rasionalitas). Panduan naqli berfungsi sebagai pedoman normatif yang diturunkan melalui wahyu, sedangkan akal (aql) digunakan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai situasi ekonomi yang terus berkembang. Pemahaman ini menjadi kunci dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta menjawab tantangan zaman.
Selain itu, peran lembaga perekonomian syariah sangat signifikan dalam merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sejarah mencatat bahwa pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin, kebijakan ekonomi berbasis keadilan dan kesejahteraan sosial telah diterapkan, mulai dari pengelolaan zakat, baitul mal, hingga distribusi kekayaan yang merata.
Artikel ini akan menguraikan konsep Syumuliatul Islam dalam ekonomi, hubungan antara panduan wahyu dan penalaran akal dalam sistem ekonomi Islam, serta peran lembaga perekonomian syariah dengan merujuk pada kebijakan ekonomi di masa Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin.
Islam sebagai Ajaran yang Komprehensif
Sebagai sebuah pandangan kehidupan, Islam memancarkan panduan kehidupan yang komprehensif. Tidak sekedar mengatur urusan spiritual yakni hubungan manusia dengan tuhan melainkan juga memberikan panduan pada aspek material yakni hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan juga dengan manusia termasuk mahluk lainnya.
Islam adalah Agama (ad-Din) yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri dan dengan sesamanya.
Berdasar pengertian di atas maka ajaran Islam dapat dikatakan memiliki tiga dimensi :
- Peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan individu dengan Penciptanya (Allah SWT), seperti ibadah, baik shalat, puasa, zakat, haji maupun jihad.
- Peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan individu dengan dirinya sendiri, seperti hukum pakaian, makanan, minuman dan akhlak, yang mencerminkan sifat dan tingkah-laku seseorang.
- Peraturan (sistem) yang menyangkut hubungan dengan orang lain, seperti masalah bisnis, pendidikan, sosial, pemerintahan, politik, sanksi hukum dan lain-lain. Ketika seluruh aspek interaksi di atas diatur dengan syariat Islam, berarti orang tersebut telah mengimplementasikan tuntunan akidah Islam dengan benar.
Sistem Syariat Dan Penalaran A’qli Dalam Konsep Ekonomi
Problem ekonomi adalah problem natural yang akan dihadapi manusia sebagai konsekuensi dari manifestasi fitrah dasar dan interaksi yang terjadi di antara mereka. Manusia sejak lahir memiliki kebutuhan hidup dan juga sejumlah naluri yang apabila tidak diatur maka akan menimbulkan kekacauan. Semakin kompleks interaksi manusia, semakin kompleks masalah yang ditimbulkan. Problem sosial, problem hukum, problem kekuasaan, problem ekonomi dan lainnya. Di antara masalah kehidupan yang sangat dominan adalah ekonomi. Islam sebagai pandangan dan panduan hidup yang komprehensif sudah tentu memiliki pandangan dan ajaran terhadap persoalan ekonomi.
وَنَزّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلّ شَيْءٍ
“Dan Kami turunkan kepada kamu Kitab ini untuk menerangkan semua perkara.” (Q.s. An-Nahl: 89).
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُاْلِسْلَمَ دِينًا
“Hari ini telah Aku sempurnakan agama kamu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku untukmu, serta Aku ridhai Islam sebagai agama kamu.” (Q.s. Al-Mâidah: 03).
Kedua nash ini menyiratkan kesempurnaan Islam. Maka dalam memecahkan problem ekonomi, secara norma bisa digali dari sumber-sumber ajaran Islam. Namun tidak semua nash syariat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah membahas seluruh persoalan kehidupan manusia secara mendetail. Sebagian besar nash tersebut bahkan hanya menjelaskan hukum-hukum tertentu secara global (mujmal) dengan makna-makna yang bersifat umum (ma’ani ‘ammah). Karena itu perinciannya diserahkan pada mekanisme ijtihad para mujtahid, yaitu ketika bentuk dan makna yang bersifat global dan umum tersebut hendak diimplementasikan sesuai dengan kondisi kasus-perkasus pada setiap waktu dan tempat.
Oleh karena itu untuk mendapat gambaran bagaimana Islam memberikan panduan perihal ekonomi atau dengan kata lain bagaimana gambaran sistem ekonomi Islam, maka mesti merujuk kepada sumber-sumber ajaran Islam serta Ijtihad para mujtahid jika panduan-panduan Islam berkenaan ekonomi masih bersifat global. Panduan naqli berfungsi sebagai pedoman normatif yang diturunkan melalui wahyu, sedangkan ijtihad digunakan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai situasi ekonomi yang terus berkembang. Namun sudah barang tentu untuk mendapatkan gambaran utuh akan konsep dan praktik ekonomi Islam maka perlu juga dikemukakan sejarah terbentuknya konsep dan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah saw dan khulafaur rasyidin
Sejarah Terbentuknya Konsep Dan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Rasulullah Saw Dan Khulafaur Rasyidin
Perekonomian Islam pada masa Rasulullah SAW
Munculnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Pada saat di Makkah Rasullah saw. mengemban tugas menguatkan pondasi akidah kaum muslim. Rasulullah di Makkah hanya berposisi sebagai pemuka agama. Sedangkan ketika hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi, namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian (Karim, 2002).
Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran al-Qur’an. Al-Qur’an telah meletakkan dasar-dasar ekonomi. Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros dalam semua urusan duniawi termasuk masalah ekonomi adalah kekuasan tertinggi hanyalah milik Allah swt. semata (QS, 3: 26, 15:2, 67:1) dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi (QS, 2:30, 4:166, 35:39), sebagai pengganti Allah di muka bumi, Allah melimpahkan urusan bumi untuk dikelola manusia sebaik-baiknya (Karim, 2002).
Dalam sistem ekonominya, Islam mengakui kepemilikan pribadi, Dalam mencari nafkah kaum muslimin berkewajiban mencara nafkah yang halal dan dengan cara yang adil. Rasulullah pun menganjurkan mencari nafkah yang baik adalah melalui perniagaan dan jual beli. Dalam berniagaan Rasulullah melarang mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak bermoral. Islam tidak mengakui perbuatan menimbun kekayaan atau mengambil keuntungan atas kesulitan orang lain. Di sisi lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam, misalnya judi, menimbunan kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, korupsi, bunya, riba dan aktivitas-aktivitas yang sejenisnya (Karim, 2002).
Pada zaman Rasulullah, sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang biasa oleh orang orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik praktik tidak fair dalam perekonomian tersebut. Karena riba didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi yang nyata, dan Islam melarang bentuk eksploitasi apapn “apakah itu dilakukan oleh orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, oleh penjual terhadap pembeli, oleh majikan terhadap budak, oleh laki-laki terhadap wanita, dan lain sebagainya.” Al-Qur’an pun menyebut, “Dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan (riba) untuk menambah kekayaan manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah” (QS, 30: 39).
Maka untuk menghilangkan riba ini, al-Qur’an memberi solusi dengan cara zakat, shodaqah dan sejenisnya. Ini ditandai dengan diwajibkannya shadaqah fitrah pada tahun kedua hijriyah atau lebih dikenal dengan zakat fitrah setiap bulan ramadhan datang, yang didistribukan kepada para fakir, miskin, budak, amil (pengurus zakat), muallaf dan lain-lain. Sebelum diwajibkannya zakat, pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusu atau ketentuan hukumnya. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijrah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun Rasulullah saat itu meliputi pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas dan tingkat persentase zakat untuk barang-barang yang berbeda beda (Karim, 2002).
Tatanan ekonomi negera madinah sampai tahun keempat hijrah, pendapatan dan sumber dayanya masih relatif kecil. Kekayaan pertama datang dari banu Nadzir, kelompok ini masuk dalam pakta Madinah tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha membunuh Rasulullah saw. nabi meminta mereka meninggalkan kota Madinah, akan tetapi mereka menolaknya, Nabipun mengerahkan tentara untuk mengepung mereka. Pada akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju baja. Semua milik Banu Nadzir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah saw. sebagaimana ketentuan yang sampaikan Allah dalam al-Qur’an, kaerena mereka mendapatkan tanpa peperangan. Rasulullah pun membagikan tanah-tanah ini kepada kaum fakir miskin dari golongan anshar dan muhajirin. Sedangkan bagian Rasulullah diberikan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhannya (Sudarsono, 2002).
Aset pemerintahan Islam Madinah juga didapat dari Khaibar, yang terlah ditaklukkan pada tahun ke-7 hijrah. Setelah pertempuran satu bulan mereka menyerah dengan syarat tidak meninggalkan tanah mereka. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma. Mereka meminta izin untuk tetap tinggal di Khaibar. Rasulullah mengabulkan permintaan mereka dan memberikan kepada mereka setengah bagian hasil panen dari tanah mereka. Sahabat Nabi bernama Abdullah Rawabah biasanya daang tiap tahun untuk memperkirakan hasil produksi dan membaginya menjadi dua bagian yang sama banyak. Hal itu terus berlangsung selama masa pemerintahan kepemimpinan Rasulullah saw. dan Abu Bakar al-Shiddiq (Sudarsono, 2002).
Pada intinya, pada zaman awal-awal Islam pendapatan yang didapatkan oleh negara Islam Madinah masih sangat kecil. Di antara sumber pendapatan yang masih kecil itu berasal dari sumber sumber, di antaranya: rampasan perang (ghanimah),tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim, khumuz atau rikaz (harta karun temuan pada periode sebelum Islam), wakaf, nawaib (pajak bagi muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, amwal fadhla (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), zakat fitrah, kaffarat (denda atas kesalahan yang dilakukan seorang mislim pada acara keagamaan), maupun sedekah dari kaum muslim dan bantuan-bantuan lain dari para shahabat yang tidak mengikat.
Perekonomian Islam para Masa Khulafa’ al-Rasyidin
a. Masa Abu Bakar
Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Abu Bakar mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua tahunan. Dalam kepemimpinannya Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang Riddah (perang melawan kemurtadan) (Yatim, 2000).
Sebelum menjadi Khalifah Abu Bakar tinggal di Sikh yang terletak di pinggiran kota Madinah. Setelah berjalan 6 bulan dari kekhalifahannya, Abu Bakar pindah ke pusat kota Madinah dan bersamaan dengan itu sebuah Baitul Mal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal ini. Abu Bakar diperbolehkan mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2000 atau 2500 dirham dan menurut keterangan 6000 dirham per tahun (Al-Usairy, 2006).
Namun di sisi lain, beberapa waktu menjelang wafatnya Abu Bakar, ia banyak menemui kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga ia menayakan berapa banyak upah atau gaji yang telah diterimanya. Ketika diberitahukan bahwa jumlah tunangannya sebesar 8000 dirham, ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan kepada negara. Juga, Abu Bakar mempertanyakan tentang berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama menjadi khalifah. Ketika diberitahukan tentang fasilitasnya, ia segera menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya nanti (Karim, 2004).
Dalam menjalankan pemerintahan dan roda ekonomi masyarakat Madinah Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar juga mengambil langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui (a’rabi) yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan membayar zakat sepeninggal Rasulullah saw. Dalam kesempatan yang lain Abu Bakar mengintruksikan pada pada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung, atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi kelebihan pembayaran atau kekurangan penerimaan zakat. Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa (Karim, 2006)
Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta baitul mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah saw. dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum Muslimin diberikan bagian hak yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan (Karim, 2006).
b. Masa Umar bin Khattab
Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Untuk pertama kalinya, pergantian kepimpinan dilakukan melalui penunjukan. Berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka sahabat memutuskan untuk menunjuk Umar bin al-Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Keputusan tersebut diterima dengan baik oleh kaum Muslimin. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai Khalifah Khalafati Rasulillah (Pengganti dari Pengganti Rasulillah). Umar juga memperkenal istilah Amir al-Mu’minin (Komandan orang-orang yang beriman) kepada para sahabat pada waktu itu (Yatim, 2000).
Pemerintahan umar berlangsung sepuluh tahun. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Umar, termasuk dibidang perekonomian pemerintah. Pada masa Umar ini banyak daerah-daerah disekitar Arab telah dikuasai Islam, termasuk daerah Persia dan Romawi (Syiria, Palistina dan Mesir) (Karim, 2006).
Dalam pemerintahannya ini, banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim pada waktu itu, di antaranya: Pertama, pendirian Lembaga Baitul Mal. Seiring dengan perluasan daerah dan memenangi banyak peperangan, pendapatan kaum muslimin mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya, agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah mengadakan musyawarah dengan para pemuka sahabat, maka diputuskan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, akan tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat didasarkan atas musyawarah. Dalam pemerintahan Khalifah Umar, Baitul Mal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namun demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul Mal untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, tunjangan Umar sebagai Khalifah untuk setiap tahunnya adalah tetap, yakni sebesar 5000 dirham, dua stel pakaian yang biasa digunakan untuk musim panas (shaif) dan musim dingin (syita’) serta serta seekor binatang tunggangan untuk menunaikan ibadah haji (Karim, 2004).
Pada masa ini harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum Muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar; membiayai penguburan orang-orang miskin; membayar utang-utang yang bangkrut; membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu, seperti memberikan pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, seperti kasus Hind bint Ataba (Karim, 2004).
Kedua, Pajak Kepemilikan tanah (Kharaj). Pada zaman Khalifah Umar, telah banyak perkembangan admistrasi dibanding pada masa sebelumnya. Misal, kharaj yang semula belum banyak di zaman Rasulullah tidak diperlukan suatu sistem administrasi. Sejak Umar menjadi Khalifah, wilayah kekuasan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Pertanyaan yang paling mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang akan diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan tersebut. Para tentara dan beberapa sahabat terkemuka menuntut agar tanah hasil taklukan tersebut dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kaum Muslimin yang lain menolak pendapat tersebut (Karim, 2004).
Dari berbagai perdebatan dan musyawarah itu akhirnya Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai fai, dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang. Sayyidina Ali tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena sedangan menggantikan posisi Umar sebagai Khalifah di Madinah. Diriwayatkan bahwa Ali tidak sependapat dengan pandangan Umar seluruhnya. Ia juga berpendirian bahwa seluru pendapatan Baitul Mal harus didistribuskan seluruhnya tanpa menyisakan sedikitpun sebagai cadangan (Karim, 2004).
Umar bin Khattab menyadari bahwa sektor pertanian sangat signifikan dalam membangkitkan perekonomian negara. Oleh karena itu, ia mengambil langkah-langkah pengembangannya dan juga mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang itu. Dia menghadiahkan kepada orang-orang yang bekerja dibidang itu. Tetapi siapa saja yang selama 3 tahun gagal mengolahnya yang bersangkutan akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Orang-orang yang mengungsi, pada waktu terjadi invasi dapat dipanggil kembali dan dinyatakan boleh menempati kembali tanah mereka. Abu Yusuf menceritakan tentang keinginan Khaliah memajukan dan membantu pengembangan pertanian. Pada waktu invansi ke Syiria seorang tentara Muslim dalam perjalanan merusak tanamannya. Mendengar pengaduan ini, khalifah segera memberi ganti rugi sebesar 10.000 dirham (Sudarsono, 2002).
Ketiga, Zakat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekayaan yang dimiliki negara Madinah sudah mulai banyak, berbeda pada awal-awal Islam. Pada zaman Rasulullah, jumlah kuda yang dimiliki orang Arab masih sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh Kaum Muslimin. Misalkan, dalam perang badar kaum Muslim hanya mempunyai dua kuda. Pada saat pengepungan suku Bani Quraizha (5 H), pasukan kaum Muslimin memiliki 36 Kuda. Pada tahun yang sama, di Hudaybiyah mereka mempunyai sekitar dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas maka seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum Muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat (Karim, 2006).
Pada generasi selanjutnya, kuda-kuda sudah mulai banyak, di Syiria Misalkan, kuda-kuda sudah mulai diternakkan secara besar-besaran di Syiria dan di berbagai wilayah kekuasan Islam lainnya. Beberapa kuda memiliki nilai jual tinggi, bahkan diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Tabhlabi diperkirakan bernilai 20.000 dirham dan orang-orang Islam terlibat dalam perdagangan ini. Karena maraknya perdagangan kuda, mereka menanyakan kepada Abu Ubaidah, Gubernur Syiria ketika itu, tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak. Gubernur memberitahukan bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian mereka menguslkan kepada Khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas keduanya tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Mereka kemudian mendatangi kembali Abu Ubaidah dan bersikeras ingin membayar. Akhirnya, Gubernur menulis surat kepada Khalifah dan Khalifah Umar menanggapinya dengan sebuah instruksi agar Gubernur menarik zakat dari mereka dan mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak. Sejak saat itu, zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar atau atas dasar ad valorem, seperti satu dirham untuk setiap empah puluh dirham (Karim, 2004).
c. Masa Utsman bin Affan
Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah wafatnya Umar bin Khatab. Perluasan daerah kekuasaan Islam yang telah dilakukan secara masif pada masa Umar bin Khattab diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasainya, seperti Balkan, Kabul, Grozni, Kerman dan Sistan. Setelah negera-negara tersebut ditaklukkan, pemerintahan Khalifah Utsman menata dan mengembangkan sistem ekonomi yang telah diberlakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Utsman mengadakan empat kontrak dagang dengan negara-negara taklukan tersebut dalam rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman membentuk armada laut kaum Muslimin di bawah komando Muawiyah, hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania (Sudarsono, 2002).
Kebijakan lain yang dilakukan Utsman terkait perekonomian adalah tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal pengeloaan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Di sisi lain, Utsman berpendapat bahwa zakat hanya dikenakan terhadap harta milik seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensin (Karim, 2004).
Ada perbedaan antara kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan dengan sebelumnya. Utsman tidak memiliki kebijakan kontrol harga. Pada khalifah sebelumnya, ia tidak menyerahkan tingkat harga sepernuhnya kepada pada pengusaha, tetapi berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit dijangkau sekalipun. Utsman bin Affan berusaha mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh kaum Muslimin di setiap selesai melaksanakan shalat berjamaah (Karim, 2004).
d. Masa Ali bin Abi Thalib
Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai gelar karramahu wajhah. Ia menikah dengan putri Rasulullah Fatimah al-Zahra dikarunia dua putra yaitu Hasan dan Husain. Di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada sama pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi hari kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi (Karim, 2006).
Ada persamaan kebijakan ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib dengan khalifah sebelumnya. Pada masa Ali alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Utsman dihilangkan karena sepanjang garis pantai Syiria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah. Namun demikian, dengan adanya penjaga malam dan patroli yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar, Ali membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut syurthah dan pemimpinnya diberi gelar shahibu al-sulthah (Karim, 2006).
Bentuk Dan Fungsi Lembaga Ekonomi Pada Masa Awal Islam
Dari gambaran sejarah di atas dapat disimpulkan bagaimana bentuk dan fungsi lembaga ekonomi pada masa awal Islam. Urusan perekonomian dikelola oleh negara melalui kebijakan dan keputusan-keputusan Nabi Saw dan para khalifah selanjutnya. semua pendapatan negara dikumpulkan dalam Baitul Mal, kemudian digunakan untuk mendanai berbagai pos negara. Setiap alokasi dana dari Baitul Mal diputuskan berdasar pertimbangan para Khalifah dan Ijtihadnya.